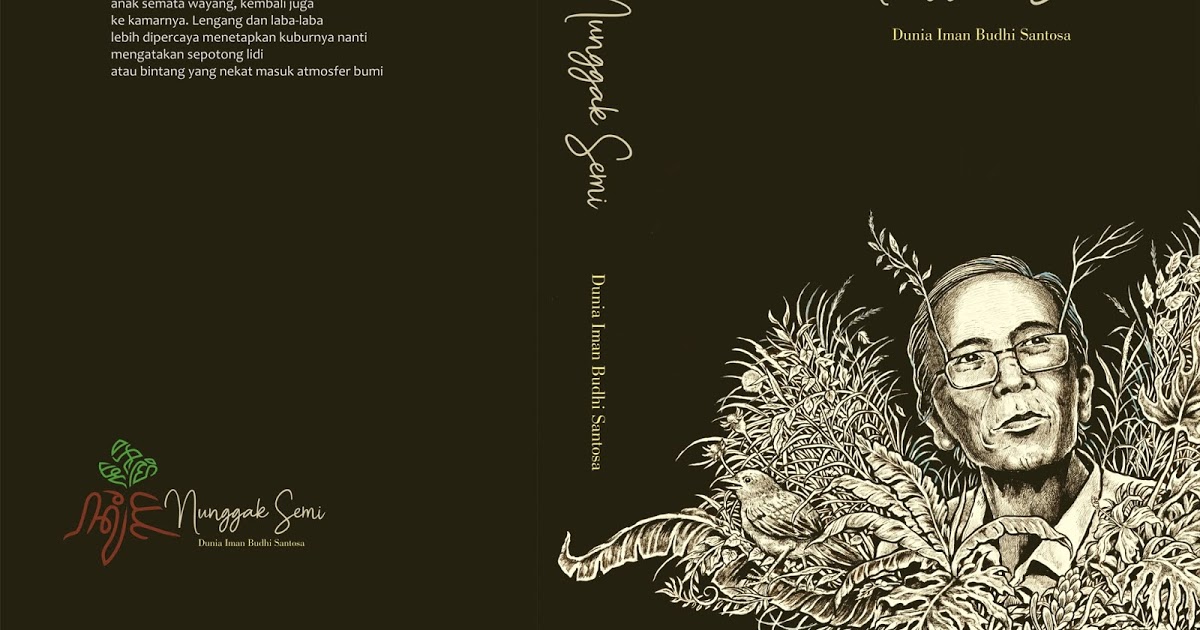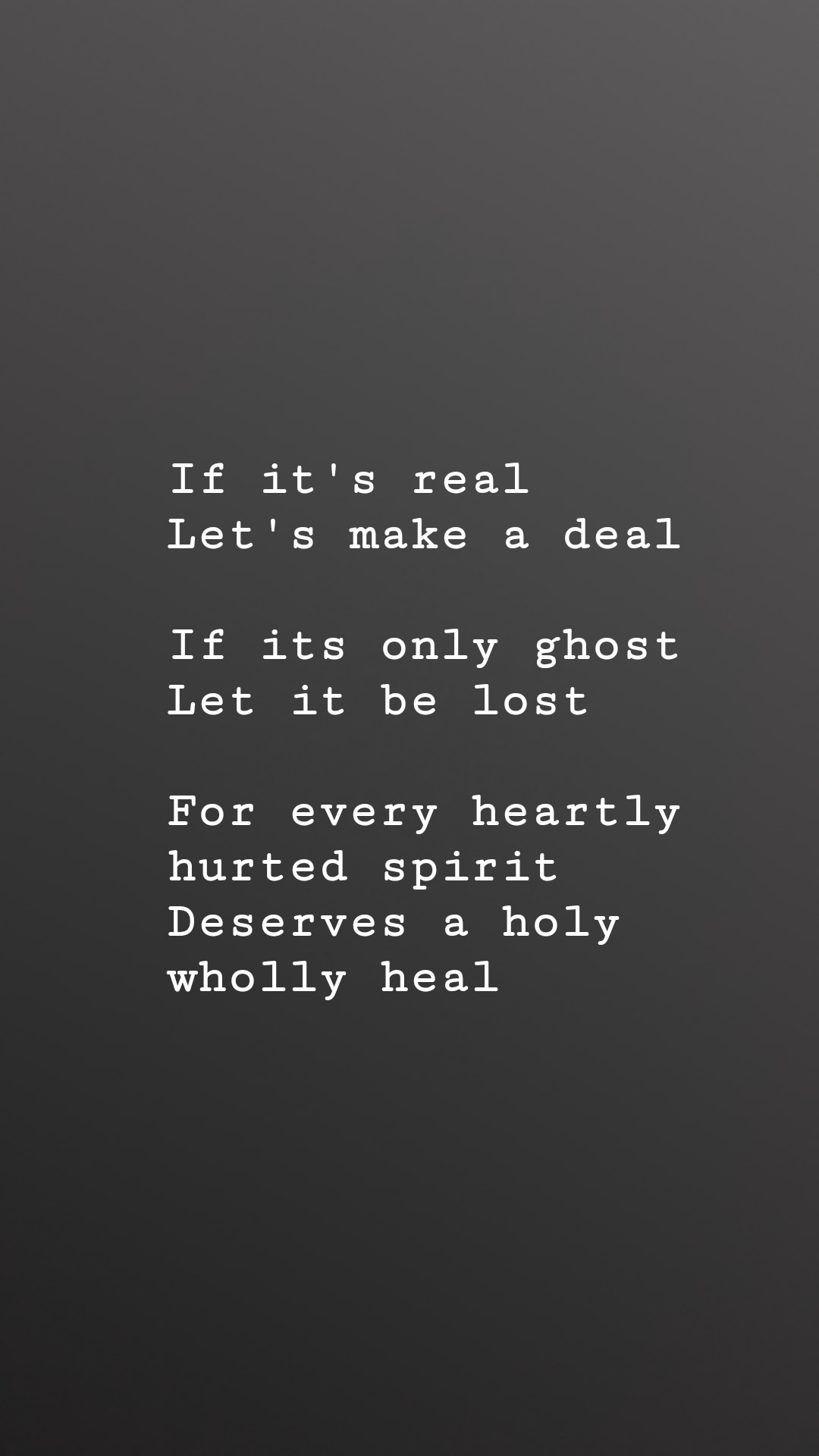Terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada Cak Kandar, kang mas sedulur sinarawedi, dan Panitia Penyusunan dan Penerbitan Buku Iman Budhi Santosa: Sebuah Obituari1 yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk turut serta dalam penulisan yang dipersembahkan bagi Romo Iman Budhi Santosa.
Jujur tidak mudah.
Bukan karena tidak mau atau merajuk meminta tambahan waktu. Saya merasa punya banyak hutang, PR, perintah uwis ta, catheten! dari Romo Iman yang belum saya setorkan kepada beliau hingga akhir hayatnya. Ada rasa sesal yang mendalam karena belum sempat nggurokke hasil catatan ke pada beliau. Ada perasaan bersalah sedemikian rupa yang membuat saya mulur-mungkret menyelesaikan tulisan ini.
Ada banyak kenangan, wejangan, momen puitik bersama Romo Iman yang sama-sama ingin kita tumpahkan sekadar melonggarkan sedikit sesak di dada. Namun saya sadar “ada kesedihan yang tak bisa dicairkan dengan kata-kata” dan “duka tak bisa disembuhkan dalam sekejap oleh kehadiran tetangga dan sanak kerabat”2 atas kepergian Romo Iman. Saya percaya kita semua menanggungnya. Untuk hal-hal yang masih belum tuntas tersebut biarlah itu menjadi PR pribadi, sumber energi untuk terus ngematke, nyatheti. Bukan untuk apa-apa, bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk ngugemi dhawuh
“sing ati-ati…
amerga kesandhung ing rata,
kebenthus ing tawang dalane ora mung siji.”
Sebisanya saya belajar dari kesabaran Romo untuk tidak gage-gage, nuruti kramadangsa, ‘memaksa’ orang lain membaca catatan yang belum jadi.
Dibandingkan sedulur yang sempat mengenal Romo Iman dari dekat, saya termasuk yang singkat. Saya bukan sastrawan apalagi penyair. Boleh dikata saya hanyalah santri kalong. Datang ketika hati terasa garing dan kosong. Sowan ngalap berkah dari sisa kopi dan tegesan. Negesi paite kahanan. Duh!
Perkenalan intens dengan Romo Iman berlangsung sejak saya ikut rewang-rewang di Majalah Sabana tahun 2015 edisi 6, melanjutkan jejak Cak Kandar yang mandegani edisi-edisi sebelumnya. Saya benar-benar beruntung sempat berada di ruang dan waktu yang sama bersama sebagian Orang-Orang Malioboro, menyaksikan dari dekat energi paseduluran dari Mbah Nun, Romo Iman, Pak Teguh, Pak Eka, Pak Budi Sardjono, Pak Parno, Pak Mustofa W Hasyim. Biasanya mbak Ririn yang rajin mencatat. Saya hanya setor kuping.
Kisah tentang Persada Studi Klub, hampir-hampir menjadi urban-legend bagi pandemen sastra di penjuru nusantara. Sudah banyak orang yang mencatat tentang kehebatan orang-orangnya, lingkar pengaruhnya, struktur relasi kebudayaannya, metode Pendidikan sastra, dan lain sebagainya. Saya tak hendak ‘nguyahi segoro’ soal itu. Saya lebih tertarik menelisik atmosfir macam apa yang menyelimuti Yogyakarta sehingga mampu menyatukan pemuda dari berbagai latar belakang. Bagaimana Malioboro menjadi melting pot antara Poros Bulaksumur dengan Poros Gampingan.
“Saat itu banyak orang sudah mulai bosan, jenuh dengan keadaan,” kata Romo.
Serupa meski tak sama dengan yang kita alami setahun terakhir ini. Kita merasakan sendiri betapa bosannya diperintah mengurung diri di rumah saja saja karena ancaman virus Covid19. Bedanya, generasi Romo Iman bosan dicekam ketakutan paska pembantaian 1965, jenuh dengan kondisi perpolitikan, kelaparan, kemiskinan, dan teror pembunuhan.
Romo Iman sendiri, sekali tempo, pernah bercerita bagaimana ia sebagai pelajar saat itu dilatih memegang senjata. Kiranya itu pula yang membuat Romo Iman bersikap tegas emoh membahas lebih detil peristiwa seputar 65. Dalam puisi berjudul “Dalam Gelap” berangka tahun 1969, Romo Iman mencatat,
“Ketika itu angin malam di luar pagar seseorang melintas, sambil berdoa, masuk ke halaman
Untuk siapakah akhirnya peluru ini
Sebab musuh kita adalah diri sendiri
Saling berbunuhankah sebetulnya, Tuhan,
antara diriku dan engkau di medan nafsu,
sebelum lampu-lampu padam
Demikian, kira-kira, kita bisa meraba-raba lanskap energi semestanya.
Sebagai jamaah Maiyah, justru dari Romo Iman saya lebih mengenal Mbah Nun. Bodohnya saya menanyakan sesuatu yang jawabannya seterang bayang-bayang di terik siang. “Macan tenan cah kae!” demikian komentar Romo Iman ketika saya memberanikan diri bertanya kehidupan Cak Nun di masa muda kok bisa seproduktif itu menghasilkan tulisan.
Kalau boleh mengumpamakan, Romo Iman dan Mbah Nun ibarat reog ponorogo. Perpaduan indahnya Burung Merak dan tenangnya Macan. Ini bukan sikap memitos-mitoskan atau mengkultuskan, sebagaimana sering dituduhkan kepada orang-orang Maiyah. Justru dari cerita-cerita Romo Iman, saya lebih jernih memandang manusia manusiawinya Cak Nun, Maiyah, Jamaah, ‘bedhes-bedhes’ seperti saya, dan segala yang dipersangkakan terhadapnya. Setidaknya saya mencatat 3 persamaan dari beliau berdua yang seolah sudah ginaris dalam perjanjian jiwa: Sosok Ibu, Umbu, Lelaku.
Sekali lagi saya belajar menginsyafi kasunyatan.
Di luar pertemuan redaksi Majalah Sabana yang lebih mirip klangenan saudara seperguruan, saya sesekali datang ke Dipowinatan untuk setor dongeng atau ngudari reribet. Kadang bersama teman-teman Sabanada (Sabana Muda), sebutan yang sebenarnya kami berlima (Mbak Ririn, Anggarista, Mbak Suci, plus Irul) buat-buat sendiri karena seringnya hanya bisa melongo ketika rapat bersama Bapak-Bapak PSK. Momen yang paling ngangeni dari sowan ke Padepokan Sor Sawo adalah mendengarkan Romo Iman membacakan puisi atau pitutur ibu. Angin serasa berhenti, ikut mendengarkan. Irul selalu meneror, mengingatkan Romo untuk menagih PR catatan.
Perihal kepenyairan Romo Iman, tak ada yang meragukan. Tak perlu pula dimitos-mitoskan. Tapi soal menafsir-nafsirkan kehidupan penyair, kita perlu mawas diri. Dalam beberapa kesempatan, Romo Iman sering rasan-rasan tentang kecenderungan para akademisi sastra yang menghubung-hubungkan PSK, Orang Malioboro, Emha, dkk dengan relasi kuasa apalagi kapital. “Memangnya di kampus UGM yang diajarkan dosen ke mahasiswa itu apa?”, “Dikit-dikit Bourdieu”, atau “Sosial kok modal?! Piye toh iki?!”
Saya tidak tahu apakah berondongan pertanyaan-pertanyaan itu dilontarkan juga kepada para cerdik cendekia yang datang padanya. Mungkin beliau me-muntap-kan itu karena tahu saya pernah kuliah di Bulaksumur. Saya yang bukan mahasiswa Fakultas Sastra merasa mendapatkan peluru nyasar.
Ya wis, trimah mawi pasrah. Kasunyatan tak bisa dibantah.
Kesan saya, Romo Iman cenderung kurang menyukai penggunaan teori-teori kritik sastra meskipun Romo sendiri senantiasa menganjurkan kita untuk berpikir kritis. Baginya, kritik adalah sesuatu yang nyalawadi (mengandung aib seseorang) yang berpotensi membuat wirang (malu). Kalau pun seseorang perlu menyampaikan kritik, sebaiknya disampaikan secara pribadi, tertutup, entah melalui catatan tertulis atau disampaikan secara empat mata. Kalau lah kritik disampaikan di harapan orang lain, rumusnya harus didahului poin apresiasi minimal tiga.
Pada kesempatan lain Romo menceritakan, bahkan dengan bangga menunjukkan, draft tesis mahasiswa yang mencoba mengaplikasikan ajaran Ki Ageng Suryomentaram sebagai kerangka konsep penelitian. Ia tampak sumringah mendengar Fakultas Psikologi UGM mulai mengembangkan Teori Psikologi Nusantara. Salah satunya ajaran Ki Ageng Suryomentaram melalui Sekolah Kawruh Jiwa. Dugaan saya waktu itu, Romo Iman sekadar ingin mengganggu kemapanan teori-teori Barat yang menghegemoni nalar pikir para pembelajar sastra yang datang padanya. Ia merindukan kemandirian bangsa, khususnya Jawa, sebagaimana pernah ia diskusikan dengan Romo Kuntowijoyo bertahun-tahun silam.
Sejak 2019 saya pamit ke Romo Iman untuk agak jarang bertandang. Selama 2 tahun terakhir saya njajah desa milangkori, belajar bersama warga desa di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Betapa nyata kisah-kisah tentang Profesi Wong Cilik, Kebun Teh Medini, dan jerat-erat Tali Pati. Kalau bukan dari Romo Iman, mungkin saya tidak akan paham mengapa angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan, Pemalang, Brebes dan wilayah sekitarnya setinggi lereng kaki Gunung Slamet. Dalam Jagongan Bareng warga Desa Beluk, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, warga sedang berembug mencari tahu asal usul keberadaan Nanas Madu (Ananas comosus) yang kini jadi produk unggulan. Hingga acara selesai, ingatan kolektif warga hanya berhenti di tahun 1980an ketika sesepuh desa mulai menanam. Dari Romo Iman pula saya dapat petunjuk tentang Lenggaong, Kutil, Dombreng, dan Peristiwa Tiga Daerah selama masa revolusi mulai kabur/dikaburkan.
Justru setelah beliau pergi, setelah saya baca ulang pesan-pesan Romo, saya menemukan makna baru atas titah “Kembalilah Ke Jawa …” Romo tidak sedang mempromosikan Ki Ageng Suryomentaram hanya karena membela pemikiran saudara sebangsa. Ia sudah dan setia memberi tuladha bagaimana menerapkan kandha-takon, Junggringsaloka dalam lingkar paseduluran atau patembayatan. Bagaimana Romo menitipkan Kawruh Jiwa, meniupkan ruh pada diksi, rima, juga jeda di antara kata. Bagaimana Romo menunjukkan metode Jawa menghidupkan yang mati. Menjadi Manusia Tanpa Ciri, ngleluri harta karun nusantara melalui prosa, peribahasa dan puisi. Menjaga masa lalu untuk kita, generasi kiwari.
Yogyakarta, 10 Februari 2021
1 Setelah terbit berganti judul Nunggak Semi: Dunia Iman Budhi Santosa. Sayangnya buku dicetak terbatas dan tidak diperjualbelikan.
2 Iman Budhi Santosa dan Wage Daksinarga. 2017. “Kisah Miyem: Tragedi Anak Turutan” dalam buku Tali Pati Kisah Bunuh Diri di Gunung Kidul. Yogyakarta: Penerbit Interlude.